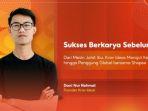Memahami Mosi Tidak Percaya DPD RI yang Dilawan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad
Istilah "mosi tidak percaya" kembali menjadi trending setelah Fadel Muhammad dicopot dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Istilah "mosi tidak percaya" kembali menjadi trending setelah Fadel Muhammad dicopot dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pencopotan Fadel Muhammad dari pimpinan MPR gegara 102 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menandatangani surat mosi tidak percaya.
Sebelum kasus Senator (DPD) Fadel Muhammad, istilah mosi tidak percaya sempat viral di media sosial lantaran pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.
Lalu apa sebenarnya makna mosi tidak pernah yang dialami Fadel Muhammad? Bagaimana penerapannya dalam sejarah dunia.
Dikutip dari kontan.co.id, dalam KBBI, kata "mosi" adalah keputusan rapat, misalnya, parlemen yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat.
Baca juga: Tamsil Linrung: Sebelum Maju Calon Wakil Ketua MPR-RI Saya Minta Restu Fadel Muhammad
Sementara, masih menurut KBBI, mosi tidak percaya adalah pernyataan tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, istilah mosi tidak percaya juga bisa digunakan dalam arti yang lebih luas.
Dalam kamus Cambridge, mosi tidak percaya adalah suatu peristiwa ketika sebagian besar anggota parlemen atau organisasi lain mengatakan, mereka tidak mendukung orang yang berwenang dan bahwa mereka tidak setuju dengan tindakan seseorang atau pemerintahan yang berwenang.
Artinya, mosi tidak percaya, adalah pernyataan atau pemungutan suara tentang apakah seseorang dalam posisi yang bertanggung jawab (pemerintah, manajerial, dan lain-lain) tidak lagi dianggap layak untuk memegang posisi itu.
Hal itu mungkin karena mereka tidak memadai dalam beberapa aspek, gagal melaksanakan kewajiban, atau membuat keputusan yang dirasa merugikan anggota lain.
Dirangkum dari HistoryExtra, mosi tidak percaya secara tradisi digunakan oleh negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer.
Baca juga: Fadel Muhammad: Hari Senin Gugatan Hukum Rp 100 Miliar Resmi Diajukan
Sebagai mosi parlementer, ini menunjukkan kepada kepala negara bahwa parlemen yang terpilih tidak lagi memiliki kepercayaan pada satu atau lebih anggota pemerintah yang ditunjuk.
Di beberapa negara, jika mosi tidak percaya dikeluarkan terhadap seorang menteri, mereka harus mengundurkan diri bersama dengan seluruh dewan menteri.
Sejarah Penggunaan
Mosi tidak percaya secara historis adalah kejadian yang cukup biasa di abad ke-19, tetapi dari tahun 1900-an hingga hari ini suara tersebut tidak terlalu sering digunakan.
Masih berdasarkan HistoryExtra, pada penggunaan mosi tidak percaya sudah dilakukan sejak 1782 ketika pasukan Britania Raya kalah dalam Pertempuran Yorktown dalam Perang Revolusi Amerika.
Mosi tidak percaya akhirnya memaksa Perdana Menteri Waktu itu, Lord North mundur dari jabatannya.
Sejak itu, ada 20 kekalahan pemerintah atas mosi percaya yang semuanya mengarah pada pembubaran atau pengunduran diri.
Di Indonesia, mosi tidak percaya sering digunakan dalam parlemen terutama di masa Indonesia sebelum periode demokrasi terpimpin, karena sebelum masa itu Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Pada masa Indonesia periode demokrasi liberal, banyak kabinet pemerintahan yang jatuh karena mosi yang diajukan oleh oposisi dalam parlemen diterima oleh keseluruhan anggota parlemen.
Contohnya adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
Dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan, seruan mosi tidak percaya dalam aksi penolak seperti UU Cipta Kerja tetap bisa dipahami sebagai simbol ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif.
Mosi tidak percaya yang diserukan demonstran dinilai Zainal juga tidak akan membuat presiden jatuh.
Pasalnya, sistem presidensial punya mekanisme berbeda dari sistem parlementer untuk melengserkan kepala pemerintahan.
Seruan mosi tidak percaya di Indonesia sebagai luapan ketidakpuasan terhadap pemerintah sekilas mirip dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dan Brasil.
Pada 1992 ketika ekonomi memburuk, rakyat AS menyerukan mosi tidak percaya kepada Presiden George HW Bush.
Sementara itu, pada Maret 2020 lalu, jutaan warga memukul-mukul panci dan wajan dari jendela rumah sebagai ungkapan protes sekaligus ketidakpercayaan terhadap Presiden Jair Bolsonaro. Dia dianggap gagal menangani pandemi COVID-19.
Meski kini tidak dikenal, Indonesia sebenarnya pernah menerapkan mekanisme pada dekade 1950-an. Kala itu, Indonesia memang menganut sistem parlementer.
Seturut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia jilid VI (2008, hlm. 310-313) setidaknya ada dua kabinet yang dijatuhkan oleh kelompok oposisi di DPR, yaitu Kabinet Sukiman dan Kabinet Wilopo.
Pada 2010, seruan mosi tidak percaya juga menerpa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Latar pemicunya adalah skandal Bank Century.
Namun, wacana itu lindap begitu saja karena mekanisme itu memang tidak ada sistem presidensial.
Asal-Usul Mosi Tidak Percaya
Mosi tidak percaya alias motion of no confidence semula berakar dari tradisi politik di Parlemen Inggris.
Profesor sejarah dari University of Exeter Richard Toye menjelaskan bahwa mosi tidak percaya berlaku di dua lembaga dalam sistem politik Inggris, yaitu di dalam kepemimpinan partai dan Parlemen.
Dalam konteks Parlemen, mosi tidak percaya menandakan bahwa pemerintah kehilangan dukungan dari House of Commons.
“Prinsip dasarnya adalah: pemerintah harus mendapatkan kepercayaan dari House of Commons. Jika pemerintah telah kehilangan suara mayoritas di House of Commons, itu adalah isyarat kejatuhan bagi pemerintah atau pemilihan umum harus diadakan,” terang Profesor Toye sebagaimana dikutip History Extra.
Dalam konstitusi Inggris, pemerintah musti mempertahankan kepercayaan House of Commons. Jika tidak, pemerintahan dianggap tidak berjalan efektif.
Saat itulah House of Commons akan menyatakan mosi dengan seruan “Bahwa Dewan ini tidak percaya pada Pemerintahan Yang Mulia”.
Parlemen kemudian akan menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah pemerintahan tetap berlanjut atau harus diganti.
Jika partai pendukung pemerintah di Parlemen menang, maka pemerintahan akan berjalan sebagaimana biasanya.
Namun, jika kalah, pemerintah akan diberi waktu 14 hari untuk kembali meyakinkan Parlemen. Di masa itulah terjadi partai pemerintah dan oposisi saling adu kekuatan politik.
Partai oposisi juga dapat membentuk pemerintahan alternatif mereka sendiri. Jika dalam jangka waktu 14 hari itu tidak ada penyelesaian yang disepakati atau pemerintahan alternatif dari oposisi ditolak, maka pemilihan umum akan dipercepat.
“Pada titik ini, perdana menteri memberi tahu Ratu perihal tanggal pemilihan umum. Kemudian, 25 hari sebelum tanggal pemungutan suara, Parlemen akan membubarkan diri,” tulis laman BBC. Kelaziman di Inggris Belum terang betul bagaimana mekanisme mosi tidak percaya pertama kali dibuat.
Namun, setidaknya mekanisme yang mirip dengan mosi tidak percaya itu pertama kali terjadi pada 1742.
Kala itu, Perdana Menteri Robert Walpole mundur dari jabatannya setelah kalah dalam sebuah pemungutan suara di House of Commons.
Mosi yang secara terang disebut mosi tidak percaya terjadi pada 1782. Kala itu, House of Commons menyerukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Lord North karena perilakunya selama perang dengan Amerika.
Mosi itu berhasil menjatuhkan Lord North dari kursi perdana menteri.
Kejadian 1782 itu lalu menjadi preseden dalam Parlemen Inggris. Pemerintah diharapkan atau diminta mengundurkan diri atau membubarkan diri jika mereka kehilangan kepercayaan Parlemen.
Mosi tidak percaya lalu menjadi kelaziman dalam perpolitikan Inggris abad ke-19. Kali terakhir mosi tidak percaya dari Parlemen mampu memicu pemilu di Inggris terjadi pada 1979.
Kala itu, Perdana Menteri James Callaghan dari Partai Buruh menghadapi mosi tidak percaya menyusul kekalahan Referendum Devolusi Skotlandia. Seruan mosi tidak percaya digalang oleh pemimpin oposisi Margaret Thatcher.
Callaghan terpaksa mengadakan pemilihan umum yang akhirnya dimenangkan oleh Thatcher dan partainya.
(*)